Oleh: Dr. M. Harry Mulya Zein,
- Pakar Ilmu Pemerintahan, Lahir di Pandeglang, Pengajar Ilmu Admisitrasi Pemerintahan Universitas Indonesia, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kini Dewan Pakar Ilmu Pemerintahan pada Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat.
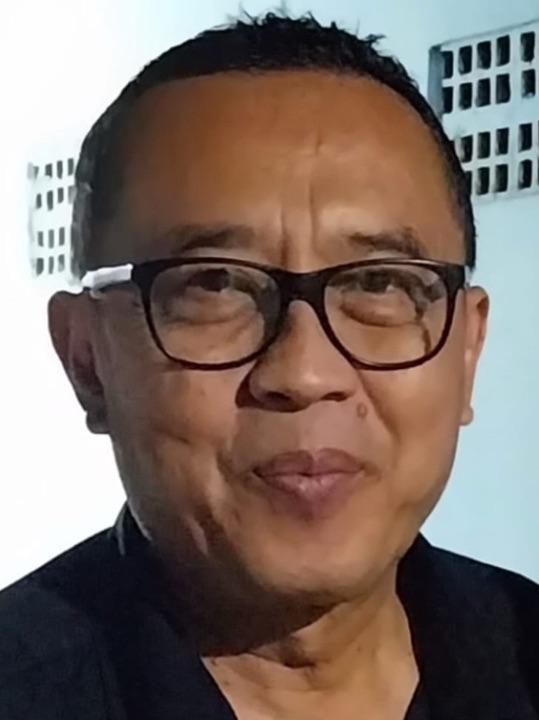
NAMA Raymond Westerling tercatat kelam dalam sejarah Indonesia. Operasi militer yang dipimpinnya di Sulawesi Selatan pada 1946–1947 menewaskan ribuan warga sipil melalui eksekusi massal tanpa proses hukum.
Westerling menjadi simbol kekerasan kolonial yang terang-benderang: senjata, darah, dan kematian hadir secara langsung di hadapan korban. Kejahatan semacam itu secara moral dan historis kita kutuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, tujuh dekade setelah kemerdekaan, muncul pertanyaan yang menggelisahkan: apakah bentuk kejahatan serupa benar-benar telah lenyap, atau justru berubah rupa? Dalam konteks ini, pembalakan hutan—terutama yang ilegal dan terorganisasi—patut dipandang bukan sekadar pelanggaran kehutanan, melainkan sebagai bentuk kekerasan struktural yang dampaknya setara secara moral dengan kejahatan Westerling.
Pembalakan hutan kerap direduksi sebagai urusan ekonomi dan tata kelola sumber daya alam. Padahal, ia adalah kejahatan yang menyerang fondasi kehidupan. Hutan bukan hanya kumpulan pohon, melainkan ruang hidup, penyangga ekosistem, dan sumber keberlanjutan generasi. Ketika hutan dibabat secara brutal, yang runtuh bukan hanya pepohonan, tetapi juga sistem sosial dan ekologis yang menopang kehidupan manusia.
Korban pembalakan hutan memang tidak selalu tewas di tempat, seperti korban Westerling. Namun, kematian akibat pembalakan hutan bersifat tertunda dan kolektif. Banjir bandang, longsor, kekeringan, krisis pangan, penyakit akibat rusaknya lingkungan, hingga kemiskinan struktural adalah rangkaian akibat yang tak terelakkan.
Dalam perspektif ini, pembalakan hutan dapat disebut sebagai kekerasan yang bekerja secara perlahan, senyap, tetapi sistematis.
Persamaan mendasar antara kejahatan Westerling dan pembalakan hutan terletak pada tiga hal. Pertama, keduanya menimbulkan korban massal. Perbedaannya hanya pada cara: Westerling membunuh secara langsung, pembalakan hutan membunuh melalui perusakan ruang hidup. Kedua, keduanya dilakukan secara terorganisasi dan terstruktur.
Pembalakan hutan bukan tindakan individual spontan, melainkan melibatkan jejaring modal, kekuasaan, dan perlindungan politik. Ketiga, keduanya terjadi dalam konteks kegagalan negara melindungi warganya.
Dalam kasus Westerling, negara kolonial adalah pelaku kekerasan. Dalam pembalakan hutan, negara sering kali hadir sebagai pihak yang lalai, permisif, atau bahkan berkompromi dengan kepentingan ekonomi.
Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, pembalakan hutan berubah dari sekadar kejahatan lingkungan menjadi kejahatan moral negara terhadap rakyatnya sendiri.
Perkembangan wacana hukum internasional menunjukkan kesadaran baru bahwa kerusakan lingkungan skala besar bukan lagi isu teknis, melainkan isu kemanusiaan.
Konsep ecocide—kejahatan terhadap lingkungan yang berdampak luas dan jangka panjang—semakin menguat sebagai kategori kejahatan serius. Meski belum sepenuhnya diadopsi dalam hukum positif nasional, arah etik dan politiknya jelas: perusakan lingkungan masif adalah pelanggaran terhadap hak hidup manusia.
Di titik inilah analogi dengan Westerling menjadi relevan. Jika Westerling adalah wajah kasar kolonialisme yang membunuh dengan senjata, maka pembalakan hutan adalah wajah halus kekerasan modern yang membunuh melalui kebijakan, pembiaran, dan keserakahan. Keduanya sama-sama merampas hak hidup, hanya berbeda dalam tempo dan metode.
Demokrasi seharusnya menjamin perlindungan terhadap warganya, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat.
Ketika pembalakan hutan dibiarkan, demokrasi kehilangan makna substantifnya dan berubah menjadi prosedur kosong. Negara yang gagal melindungi hutannya sejatinya sedang gagal melindungi masa depan rakyatnya.
Mengutuk Westerling tanpa keberanian melawan pembalakan hutan adalah paradoks moral. Sejarah kekerasan tidak hanya hidup dalam buku pelajaran, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan alam hari ini.
Jika kita sepakat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak pernah kedaluwarsa secara moral, maka pembalakan hutan pun harus ditempatkan dalam kategori dosa publik yang sama seriusnya: kejahatan terhadap kehidupan.(*)